
27 September 2008
 ...dari keseluruhan kisah yang ada, hampir-hampir tak dialurkan dengan rasa menghiba. Kemiskinan yang telah berada di titik nadir pun, terurai dengan jalinan kalimat sederhana dan nyaris apa adanya. Ketiadaan pretensi untuk menyulap kemiskinan menjadi barang yang mengkilap, adalah merupakan keistimewaan dari kumpulan cerita pendek ini...
...dari keseluruhan kisah yang ada, hampir-hampir tak dialurkan dengan rasa menghiba. Kemiskinan yang telah berada di titik nadir pun, terurai dengan jalinan kalimat sederhana dan nyaris apa adanya. Ketiadaan pretensi untuk menyulap kemiskinan menjadi barang yang mengkilap, adalah merupakan keistimewaan dari kumpulan cerita pendek ini...
(Baca selengkapnya)
Religiusitas Kemiskinan yang Tak Lagi Mengkilap
Oleh Ilung S. Enha*)
Membaca Kerebritis, ternyata tak sekedar membaca tentang kemiskinan. Sebab penggambaran – atau lebih tepatnya potret – persoalan dari ragam problematika, setting lokasi dan suasana dari situasi kehidupan mereka, benar-benar hidup dan nyaris nyata. Sehingga tak hanya wajah kemiskinan yang berputar-putar di kelopak mata kita, melainkan pula degup suara jantung dan desah nafas yang mendengus di gendang telinga, serta kita pun bisa merasakan keprihatinan dan keletihan jiwa dari “titik jenuh” orang-orang miskin.
Labirin permasalahan dari orang perorang komunitas Kerebritis, benar-benar menyodok hati yang buntu dan perasaan yang mati – terutama bagi pembaca yang masih setia untuk menyisakan dalam jiwanya sekeping nurani. Kontinuitas suspensi yang kerapkali berhenti pada titik koma, secara perspektif neurologis telah menjejalkan informasi yang sambung-menyambung, sehingga mampu menggerakkan milyaran sel saraf dalam tabung otak kita untuk segera melahirkan solusi atau setidaknya responsi dan antisipasi.
Itulah yang menyebabkan sang pengendali di pusat otak memerintahkan milyaran sel saraf tersebut, untuk mengakses situs-situs purba dan membrowsing serta mendownload file-file usang yang sudah karatan dalam lemari besi otak yang bernama memori. Setelah melalui proses diskusi yang alot di ajang debat terbuka dan forum musyawarah, maka disepakatilah kesimpulan-kesimpulan. Dari sanalah kita kemudian dibikin mengerti, bahwa orang-orang miskin adalah merupakan hasil cetakan dari sebuah sistem hidup yang timpang dan culas.
Sistem hidup itu bisa bernama perpolitikan yang busuk, atau format perekonomian yang tanpa ventilasi sedekah – sehingga mengakibatkan jurang si kaya dan si miskin tak pernah sempat untuk menyempit. Sebagai penyebab dan sekaligus akibatnya, adalah distribusi kesempatan dan fasilitas hidup yang sangat tidak berimbang. Fatalnya lagi, sistem hidup semacam itu justru disokong oleh arus komunikasi dan informasi yang senjang, wilayah perkembangan teknologi yang tak merata, dominasi kultural yang terus dipertahankan, serta sikap antipati terhadap tradisi-tradisi yang dianggap bisa “menghambat” jenjang perkembangan dan laju kemajuan zaman.
Sebab ketika dunia tengah berlari menuju sebuah peradaban global village, maka apa saja yang tak sesuai dengan kecenderungan zaman, akan dilindas dan dilibas habis sampai ke akar-akarnya. Sehingga rumusan lain mengatakan, bahwa komunitas Kerebritis adalah lahir dari orang-orang yang telah gagal dalam pergumulan pencariannya untuk dapat meningkatkan skill dan mencapai keterampilan yang baru. Maka lambat laun nasib mereka jadi terpinggirkan, sehingga sama sekali merasa asing tatkala memandang wajahnya di dalam kaca peradaban dan cermin kehidupan. Orang-orang semacam itu harus rela mengongkosi hari depannya sendiri, untuk sanggup secara terus menerus mempertahankan nasibnya di gang-gang sempit kehidupan.
Namun yang menjadi jawaban kunci dari segala kunci fenomena Kerebritis, bahwa mereka sesungguhnya terlanjur memiliki jiwa-jiwa yang miskin – akibat dari pemiskinan kultural psikologis, atau pun memang termiskinkan lantaran tak kuat menahan cercaan dari mikrofon peradaban global. Dus, untuk bisa bangkit dan bahkan dapat keluar dari komunitas Kerebritis, maka jalan utama yang harus dilalui terlebih dahulu, adalah penyadaran kembali bahwa sesungguhnya mereka masih memiliki jiwa-jiwa yang hidup. Pertahanan terakhir itulah yang sebisa mungkin harus mendapatkan penyelamatan, agar mereka tak merasa hidup sebagai orang miskin. Dengan meminjam jargon yang sudah klise; hidup boleh miskin harta, asal jiwa tetap kaya.
Dengan bekal modal kaya hati itulah, seorang Kerebritis bisa mulai menapak kembali menyongsong hari depannya yang sudah lusuh. Dengan begitu dirinya masih memiliki seutas kesempatan, untuk mencuci baju kumal kemiskinannya di dalam telaga bening nurani, mengeringkannya di matahari pikiran, serta melicinkannya dengan panasnya seterika kehendak dan harapan. Dengan mengenakan kembali baju necis kemiskinan – setidaknya bagi rasa jiwa – demikian ini, masih jauh lebih mulia ketimbang menyerahkan nasib begitu saja di atas tungku keputusasaan yang tiada berujung. Apalagi irama ratapan saat ini, suaranya sudah tak lagi begitu nyaring terdengar. Sehingga menghiba dengan sekeras-kerasnya, sudah tak lagi dijawab dengan ketulusan rasa iba.
Dan itulah yang membuat saya tertarik dengan jalinan cerita yang termaktub dalam buku ini. Sebab dari keseluruhan kisah yang ada, hampir-hampir tak dialurkan dengan rasa menghiba. Kemiskinan yang telah berada di titik nadir pun, terurai dengan jalinan kalimat sederhana dan nyaris apa adanya. Ketiadaan pretensi untuk menyulap kemiskinan menjadi barang yang mengkilap, adalah merupakan keistimewaan dari kumpulan cerita pendek ini. Seakan penulisnya berkata: biarlah potret kehidupan ini berjalan secara apa adanya. Sementara untuk memoles kemiskinan menjadi karya yang luks, biarlah itu menjadi hak LSM pemiskinan, orang-orang yang sok berjuang untuk kaum miskin, atau para selebriti entertainment kemiskinan.
Latar belakang kaca pandang semacam itulah, yang membuat saya lebih memposisikan karya ini sebagai Solilokui daripada sebagai Cerita Pendek. Apalagi penulisnya tak demikian setia dengan bentuk, alur, model penuturan, maupun isi yang seharusnya hadir di dalam sebuah Cerpen. Hanya sedikit tulisan yang bisa memenuhi “persyaratan formal” dan kriteria yang bisa dikategorikan ke dalam sebuah Cerita Pendek. Selebihnya, yang ada hanyalah berupa gugusan ide-ide yang berpendar-pendar memancar memenuhi ruang cerita dan ruang jiwa kita. Tapi gaya penuturan yang “tak sesak” dari pemotretan realitas yang nyaris nyata itulah, yang menjadi kelebihan utama karya ini.
Dan nyatanya, justru dari pemaparan semacam itulah sebuah religiusitas bisa dibangun. Sebab apalah artinya sebuah karya bila cuma berhasil menyentuh emosi, tetapi gagal menggerakkan religiusitas pembacanya? Sebuah letupan yang meledak di ruang emosi, tentu lebih merupakan sebuah teror belaka. Sementara karya yang menghembus di ruang religiusitas, adalah lebih merupakan suara kebajikan yang bijak.
Dengan kalimat yang lebih simbolik, bukankah karya yang hidup di ruang emosi bagai riak-riak ombak yang tengah menembus gelombang samudera di jiwa raya? Sementara karya yang hidup di ruang religiusitas, bagaikan sepercik ombak kecil yang tengah membelah sebuah danau yang tenang. Seperti halnya sebiji doa; akan jauh lebih terasa getarannya bila ia menjadi kerikil yang jatuh di ketenangan danau, daripada berupa batu besar yang terlempar di tengah gelombang lautan singgasanaNya.
*) Kreator intelegensia ADEC (Alternative Development & Educaion Centre), serta penulis buku “Mencari Tuhan di Warung Kopi” dan “Diary Untuk Tuhan”
Labels: Epilog

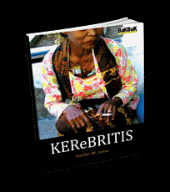




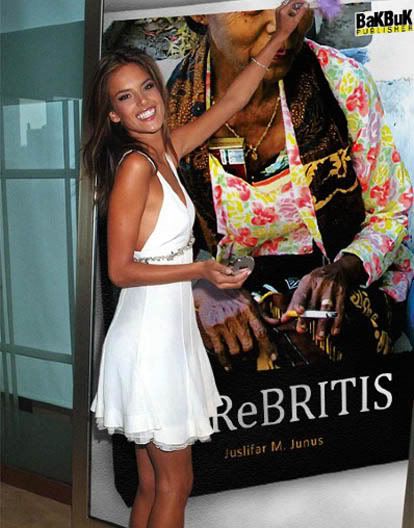

0 comments:
Posting Komentar